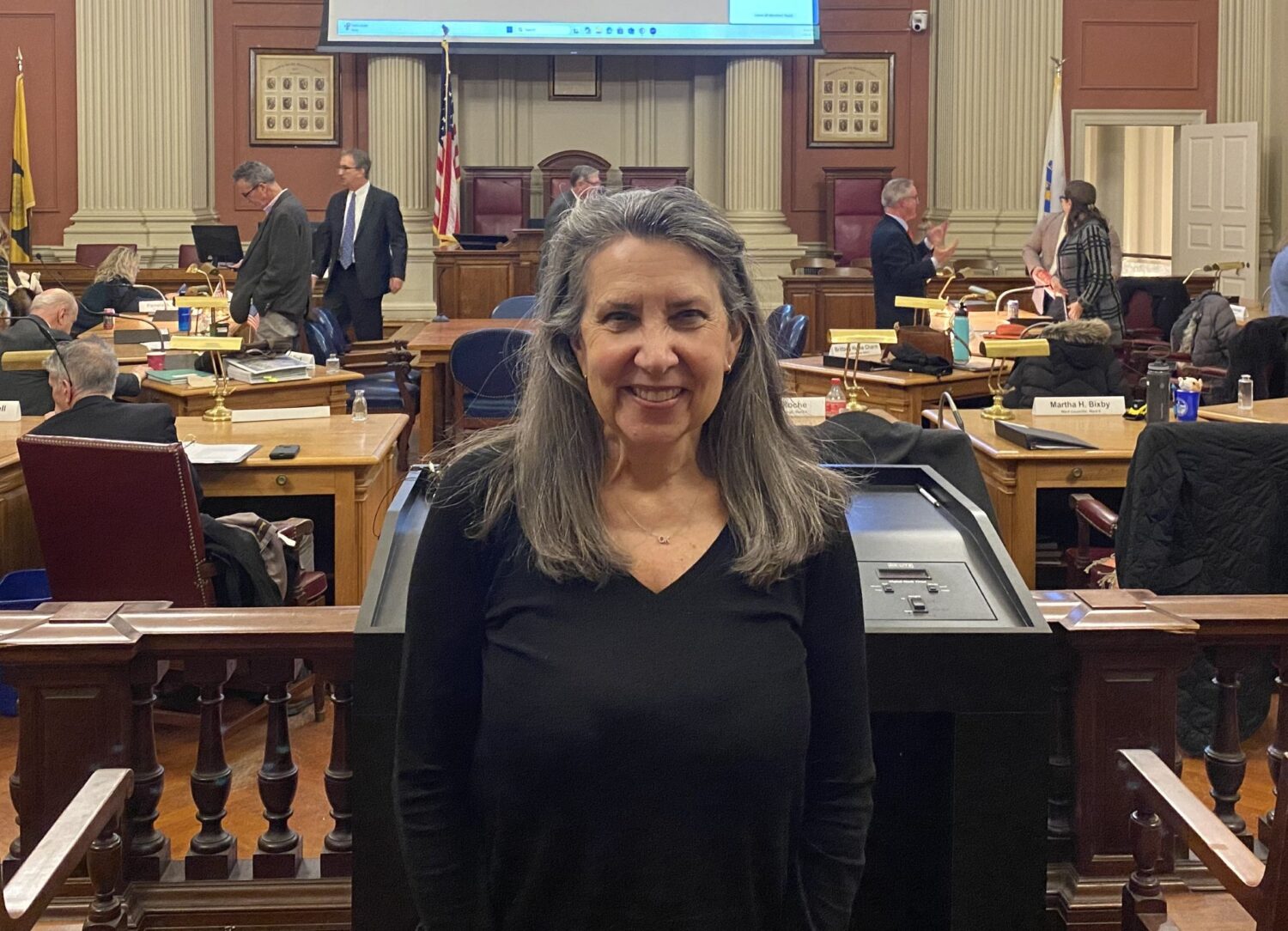Pertama kali saya menyadari bahwa saya telah kehabisan energi bukan saat krisis; tapi saat rapat staf. Mata saya kabur saat kepala sekolah membahas poin data dan kalender pacing. Saya ingat mengangguk sambil tubuhku berteriak minta istirahat. Di sekeliling saya, guru-guru menatap laptop mereka, bahu melorot dan cangkir kopi setengah kosong. Tidak ada yang berbicara kecuali diminta. Campuran apati dan bertahan hidup. Kami adalah pendidik yang berusaha untuk tetap tegak dalam sistem yang lupa bahwa kami adalah manusia.
Setelah pandemi, kelelahan telah menjadi dasar kami. Ruang kelas dipenuhi dengan kecemasan saat murid-murid kembali dengan lapisan traumanya yang baru, keluarga berjuang dengan kehilangan dan ketidakstabilan, dan pendidik menyerap semuanya. Pengembangan profesional terus berlanjut, rubrik masih penting, dan frase “self-care” dilemparkan di sekeliling seperti sebuah catatan lengket. Tetapi apa yang saya lihat dan rasakan lebih dalam dari sekadar kelelahan. Itu adalah duka, keterputusan, dan kebutuhan putus asa akan komunitas.
Jadi saya melakukan sesuatu yang kecil, mungkin bahkan radikal: Saya bertanya pada setiap anggota staf di komunitas saya apa yang mereka benar-benar butuhkan. Bukan pelatihan lain, bukan kebijakan lain, tetapi sesuatu yang mengingatkan kita siapa kita di luar kelas. Ini dimulai dengan formulir Google dan pertanyaan sederhana: Apa yang membuatmu senang?
Dalam waktu seminggu, kotak masuk saya dipenuhi dengan ide, dan dari ide-ide ini berkembang inisiatif baru yang saya sebut “Moment Komunitas Staf.” Dua kali seminggu, kami membuka pintu kelas kami satu sama lain selama akhir hari, bukan sebagai guru atau penilai, tetapi sebagai manusia.
Suatu hari Rabu, guru Spanyol kami mengubah kelasnya menjadi studio tari mini, memimpin kelas salsa yang penuh tawa dan keberanian. Beberapa hari kemudian, saya menemukan diri saya mengajarkan frasa dasar Bahasa Isyarat Amerika; suara kami digantikan oleh tawa yang bergema melalui lorong saat kami berkomunikasi dengan isyarat yang baru. Di gym, kolega lain membimbing kami melalui pose yoga, suaranya tenang mengingatkan kami untuk bernapas saat kami berusaha melepaskan ketegangan dari tubuh kami. Guru seni membuka ruangannya sebagai tempat perlindungan untuk kebebasan kreatif, membiarkan kami melukis sambil musik lembut memainkan di latar belakang. Guru bahasa Prancis mengubah kelasnya menjadi kafe Paris, lengkap dengan makanan ringan, gantungan kunci Menara Eiffel, dan undangan hangat untuk belajar frasa sederhana. Tidak ada absensi dan tidak ada mandat. Hanya kehadiran, kemampuan untuk masuk dan keluar dari suatu ruang sesuai keinginan Anda dan bergabung dalam “moments” yang benar-benar menarik bagi Anda.
Pada suatu sore, setelah salah satu acara kami, seorang kolega berpaling ke saya dan berkata, “Saya tidak menyadari betapa saya membutuhkannya sampai sekarang.” Saya juga tidak. Karena perhatian, saat dipraktikkan secara kolektif, memiliki kemampuan untuk menyulut kembali nyala, menciptakan komunitas, dan mencegah kelelahan. “Moments” ini tidak “memperbaiki” sistem kami, tetapi mereka mengingatkan kami bahwa nilai kita tidak terikat pada rencana pelajaran atau poin data kami. Kami sedang merebut kembali sesuatu yang jarang didorong oleh sekolah – kemanusiaan kami.
Klaim itu bahkan semakin jelas ketika saya bersama-sama memimpin sesi pengembangan profesional dengan seorang konselor sekolah tentang kelas yang berbasis trauma. Kami memulai dengan Adverse Childhood Experiences (ACE), yang merupakan kerangka kerja yang mengukur paparan trauma masa kecil seperti penyalahgunaan, kelalaian, dan disfungsi rumah tangga.
CDC mendefinisikan ACEs sebagai peristiwa yang berpotensi traumatis yang dapat memiliki dampak berkelanjutan pada kesehatan, perilaku, dan pembelajaran. Semakin tinggi skor ACE Anda, semakin besar risiko Anda mengalami masalah kesehatan kronis, depresi, penyakit autoimun, dan bahkan kematian dini. Namun, saat saya membaca studi-studi tersebut, satu statistik membuat saya tercengang: pendidik sendiri juga membawa skor ACE yang tinggi. Selama pelatihan, kami mengundang staf kami untuk merenungkan dan berbagi sejarah ACE mereka sendiri, dan banyak yang mendapatkan skor empat atau lebih. Beberapa kolega berbagi bagaimana pola-pola ini mencerminkan perjuangan mereka saat ini sebagai pendidik – malam tidak tidur, migrain, serangan panik, rasa bahwa mengajar kadang-kadang memicu naluri kelangsungan hidup masa kecil mereka.
Pelatihan itu mengekspos kebenaran yang jarang kita sebut: pendidik membawa trauma secara diam-diam, profesional, dan berkelanjutan. Dan jika kita tidak mengakui hal itu, sistem akan terus menuntut kami memberi dari sumur yang kosong.
The Weight We Absorb: Secondhand Trauma in Schools
Kesenjangan pandemi menunjukkan pahitnya kenyataan bahwa trauma juga merupakan bagian tak terelakkan dari pengalaman belajar. Dan pendidik, bersama dengan murid, diseret dalam arus yang sama tanpa pelindung. more informal converse lebih urang sido melakukan perawat uih wa jika murid, ngultimat kita kan man luak se tuk grak ke selow. Baumaniversitas, luwahan ilah ay sei, kofi kay hus sep tentang Laju h ilah…nu ku jari Orthepul. Saat kita tidak menangkap cerita yang tersembunyi di balik reaksi tersebut, kita berisiko salah mengartikan, dan hasilnya adalah keterputusan.
Publikasi “Mencegah Stres Traumatik Sekunder pada Pendidik” melaporkan bahwa hampir separuh pendidik mengalami tingkat stres traumatik sekunder, dengan gejala mulai dari insomnia hingga mati rasa emosional. Studi lain menemukan bahwa lebih dari 90 persen personel sekolah melaporkan tingkat stres traumatik sekunder, dan hampir separuh mengalaminya pada tingkat yang parah.
Saya melihat hal ini terjadi dalam komunitas sekolah saya: seorang guru keluar dari kelas untuk bernafas setelah menenangkan perilaku seorang murid, seorang lainnya menangis diam-diam di kelasnya setelah mendengar seorang anak mengungkapkan pelecehan, seorang pendidik lain pergi membeli makanan dan pakaian baru untuk seorang murid yang menjadi tunawisma, dan kolega lainnya pergi dengan seorang murid ke rumah sakit karena ideasi bunuh diri.
Bagi pendidik seperti saya, ini berarti bekerja dengan murid-murid yang telah mengalami trauma berulang, yang menyebabkan kita hidup dalam paparan yang konstan. Kami mendengarkan, menyerap, dan menyikapi, semua sambil mengelola IEP, merencanakan pelajaran, dan ekspektasi yang tak terucapkan untuk “tetap tenang”. Kebenaran adalah, trauma, sama seperti kebahagiaan, itu menular, dan para pendidik berada di garis depan tanpa peralatan pelindung.
What Building a Culture of Care Looks Like
Membangun budaya sekolah tidak memerlukan gebrakan besar. Itu memerlukan keberanian, kerendahan hati, dan desain yang menghormati keseluruhan diri orang.
Berikut adalah hal-hal yang saya pelajari berhasil:
1. Kesehatan yang berasal dari Dalam: Undang staf untuk memimpin sesi kesehatan seputar passion mereka. Lindungi waktu tersebut dan jangan menjadwalkan kegiatan lain di atasnya, dan jangan mengubahnya menjadi mandat. Perhatian nyata tidak bisa dipaksa. Ketika pendidik memiliki agensi dalam penyembuhan mereka, partisipasi menjadi kebahagiaan, bukan kewajiban. 2. Pengembangan profesional Berbasis Trauma yang Dimulai dari Dewasa: Sertakan refleksi ACE dalam pengembangan profesional, bukan untuk mendiagnosis tetapi untuk meningkatkan kesadaran. Gabungkan dengan pendidikan tentang dampak biologis trauma dan konsep stres sekunder. Tawarkan sumber daya, rujukan konseling, informasi EAP, dan sesi mindfulness yang berkelanjutan. 3. Lingkaran Dukungan Sebaya: Bentuk kelompok kecil, sukarela yang bertemu bulanan untuk mendengar dan merenungkan. Normalisasi kerentanan dengan melibatkan pemimpin dan guru. Kesembuhan tumbuh dalam bahasa bersama dan kepercayaan saling. 4. Kepemimpinan yang Penuh Kasih: Administrator harus memimpin dengan empati dan menciptakan struktur yang menghormati kemanusiaan: jadwal yang fleksibel, istirahat kesehatan, beban kerja yang realistis. Periksa staf, tidak tentang rencana pelajaran, tetapi tentang bagaimana keadaan mereka.
The Ripple Effect Tahun setelah kami memulai inisiatif ini dan mulai memprioritaskan hubungan, ada yang berubah. Hubungan baru terbentuk di antara orang-orang yang jarang berbicara. Kolega mulai saling memeriksa satu sama lain, bukan hanya tentang kurikulum, tetapi tentang kehidupan. Bahkan murid juga melihat perubahan dalam energi komunitas sekolah. Mereka melihat guru-guru mereka tersenyum lebih banyak, lebih banyak berkolaborasi, lebih banyak memeluk, dan memodelkan seperti apa perhatian komunitas itu.
Kami berada dalam profesi yang sering menuntut ketahanan superman. Tapi kita tidak bisa menuang dari cangkir kosong. Kesejahteraan pendidik bukanlah kemewahan; itu adalah kebutuhan. Jika kita terus mengabaikan dampak trauma, kelelahan akhirnya akan tetap tak terhindarkan, dan sekolah akan terus memiliki tingkat pergantian yang tinggi.
Membangun budaya peduli adalah tindakan perlawanan terhadap sistem yang mengukur nilai seorang pendidik dari hasil kerjanya. Ini adalah pernyataan bahwa mengajar bukan hanya usaha intelektual, itu adalah pekerjaan emosional, kerja komunitas, dan pekerjaan yang sangat manusiawi.