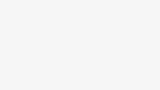Surabaya (ANTARA) – Indonesia- baik masyarakat maupun otoritasnya- tampaknya semakin tangguh menghadapi terorisme dan keyakinan radikal.
Negara telah mendefinisikan kembali dan memperkuat komitmen kuat terhadap persatuan nasional, sehingga Kepolisian Nasional (Polri) menyatakan negara bebas dari serangan teror sepanjang 2023 hingga 2025, mengutip “penegakan hukum yang melindungi.”
Namun demikian, tidak ada alasan bagi negara untuk merasa puas, terutama di tengah taktik yang terus berubah yang diadopsi oleh kelompok teroris dan radikal. Pandangan ini, hingga batas tertentu, didukung oleh fakta bahwa publik terkejut dan bingung oleh dua ledakan yang dilakukan oleh seorang minor di sebuah sekolah menengah di Jakarta Utara pada November 2025, yang melukai 96 orang.
Teror di sekolah Jakarta, seperti yang banyak disebut oleh banyak orang, seharusnya secara alamiah mendorong baik masyarakat maupun otoritas untuk melihat lebih dalam ke kecenderungan radikalisasi yang menargetkan anak-anak di bawah umur, dan untuk menyadari bahwa terorisme tidak pernah terbatas pada latar belakang agama.
Ini terjadi meskipun insiden tersebut tidak secara resmi dinyatakan sebagai serangan teror- setidaknya pada saat artikel ini ditulis.
Densus 88, yang secara luas diakui sebagai tulang punggung anti-teror Polri, baru-baru ini mengungkapkan temuan yang menunjukkan bahwa 70 warga di bawah umur diduga terpapar ekstremisme yang disebarkan melalui Komunitas True Crime (TCC).
Beroperasi secara utama secara online, TCC diduga sangat kuat meracuni anak-anak dan remaja dengan ideologi yang pada dasarnya asing bagi Indonesia, seperti Neo-Nazisme dan supremasi kulit putih- kedua ideologi ini berakar dalam sejarah kekerasan rasial dan diskriminasi sistemik dan, membuat banyak orang terkejut, meninggalkan jejak dalam ledakan Jakarta.
Berdasarkan temuan Densus 88, pengaruh TCC paling signifikan terletak di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang masing-masing menjadi rumah bagi 15, 12, dan 11 dari 70 anak yang terpapar ekstremisme- semuanya berusia antara 11 dan 18 tahun, periode yang dianggap paling rentan bagi seseorang terbawa oleh penemuan hidup yang baru, meskipun berbahaya.
Lebih mengkhawatirkan lagi adalah bahwa polisi telah mengkonfirmasi bahwa anak-anak- atau remaja, untuk lebih tepatnya- ini telah terpapar ekstremisme di luar konsumsi konten pasif. Beberapa dari mereka menunjukkan indikasi minat, dan bahkan pengetahuan, tentang senjata mematikan.
Dengan ketidakhadiran respons yang efektif, tren ini dapat memunculkan ancaman nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, semakin memperkuat kebenaran sulit untuk disangkal bahwa radikalisasi telah merasuki ruang digital- sebuah ranah yang terus berkembang yang terbukti berpengaruh dalam membentuk keyakinan, sikap, dan karakter individu dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi.
Radius Setyawan, seorang analis budaya dan media di Universitas Muhammadiyah Surabaya, mencatat fenomena ini sebagai refleksi krisis produksi nilai dalam ruang digital.
Seperti yang ditunjukkan sejarah, ideologi radikal seperti neo-Nazisme dan supremasi kulit putih telah menggerakkan kekerasan yang didorong secara rasial, terutama di Amerika Serikat dan Eropa.
Namun, dalam lingkungan digital saat ini, simbolisme yang terkait dengan ideologi ini sering kali dilepaskan dari konteks sejarah dan etika. Ekstremisme semakin mencapai audiens muda melalui media yang halus dan tampaknya tidak berbahaya seperti meme, narasi sensasional, atau diskusi komunitas online yang santai.
Dinamika ini memungkinkan simbolisme ekstremis menarik anak-anak dan remaja tanpa pemahaman mereka terhadap asal-usul ideologis atau konsekuensi sejarahnya.
Jauh dari menjadi ruang netral, ranah digital telah, hingga batas tertentu, digunakan sebagai senjata untuk menarik individu- termasuk anak di bawah umur- ke dalam kekerasan simbolis dan, potensialnya, kekerasan dunia nyata.
Langkah Antisipatif
Temuan tentang radikalisasi anak oleh Densus 88 telah mengungkapkan tantangan baru bagi sektor pendidikan Indonesia dan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan tingkat kewaspadaannya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai memperingatkan bahwa ruang digital menarik anak-anak ke dalam lingkungan yang semakin kompleks dan cepat berubah. Tanpa bimbingan, pengawasan, dan literasi digital yang tepat, ia memperingatkan, risiko paparan konten berbahaya meningkat tajam.
Sebagai respons, kantor tersebut proaktif bergerak untuk mengurangi risiko keyakinan atau dorongan kekerasan di antara siswa SMA, termasuk panggilan intensif untuk sekolah menghasilkan lingkungan yang aman di mana siswa dapat tumbuh dan berkembang.
Sama pentingnya adalah penerapan pendekatan literasi digital reflektif- memastikan bahwa siswa tidak hanya terampil dalam menggunakan gadget dan aplikasi tetapi juga mampu berpikir kritis, memahami konteks, mengidentifikasi narasi manipulatif, dan mengenali konsekuensi sosial yang lebih luas dari konten yang mereka konsumsi.
Upaya ini melengkapi inisiatif untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan meningkatkan peran konseling dan guru wali kelas dalam deteksi dini paparan ekstremis.
Pendidik didorong untuk meningkatkan sensitivitas mereka terhadap perubahan perilaku di antara siswa.
Untuk memperkuat batas digital di sekolah, pemerintah provinsi berencana untuk mengenalkan regulasi penggunaan gadget, memantau kegiatan ekstrakurikuler, memeriksa komunitas online tempat siswa berinteraksi, dan mendirikan mekanisme pelaporan yang menghindari stigmatisasi.
Pada saat yang sama, otoritas bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara sekolah dan keluarga sambil membangun kerjasama dengan kementerian terkait, lembaga keamanan, dan lembaga perlindungan anak- menanggapi akar penyebab radikalisasi daripada hanya mengandalkan tindakan reaktif atau penegakan hukum.
Inisiatif-inisiatif ini sejalan dengan upaya nasional untuk melawan indoktrinasi anak, dengan Densus 88 melaporkan lima penangkapan pada tahun 2025 dan memberikan bantuan kepada 68 anak yang terpapar ideologi kekerasan.
TCC dan kelompok serupa telah meninggalkan luka psikologis yang dalam, memaksa Indonesia untuk menghadapi dampak ekstremisme digital pada kestabilan mental dan kognitif anak-anak.
Episode ini memberikan pengingat yang membuat sadar akan bagaimana ideologi radikal dapat menyusup ke dalam ruang digital di bawah mantel yang hampir tidak terlihat.
Dalam konteks ini, pendidikan berorientasi pada dampak diharapkan dapat memelihara generasi muda Indonesia yang tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki pemikiran reflektif, empati sosial, dan ketahanan terhadap ideologi kekerasan.
Penulis: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026